Tantangan Reverse Engineering dalam Meningkatkan TKDN
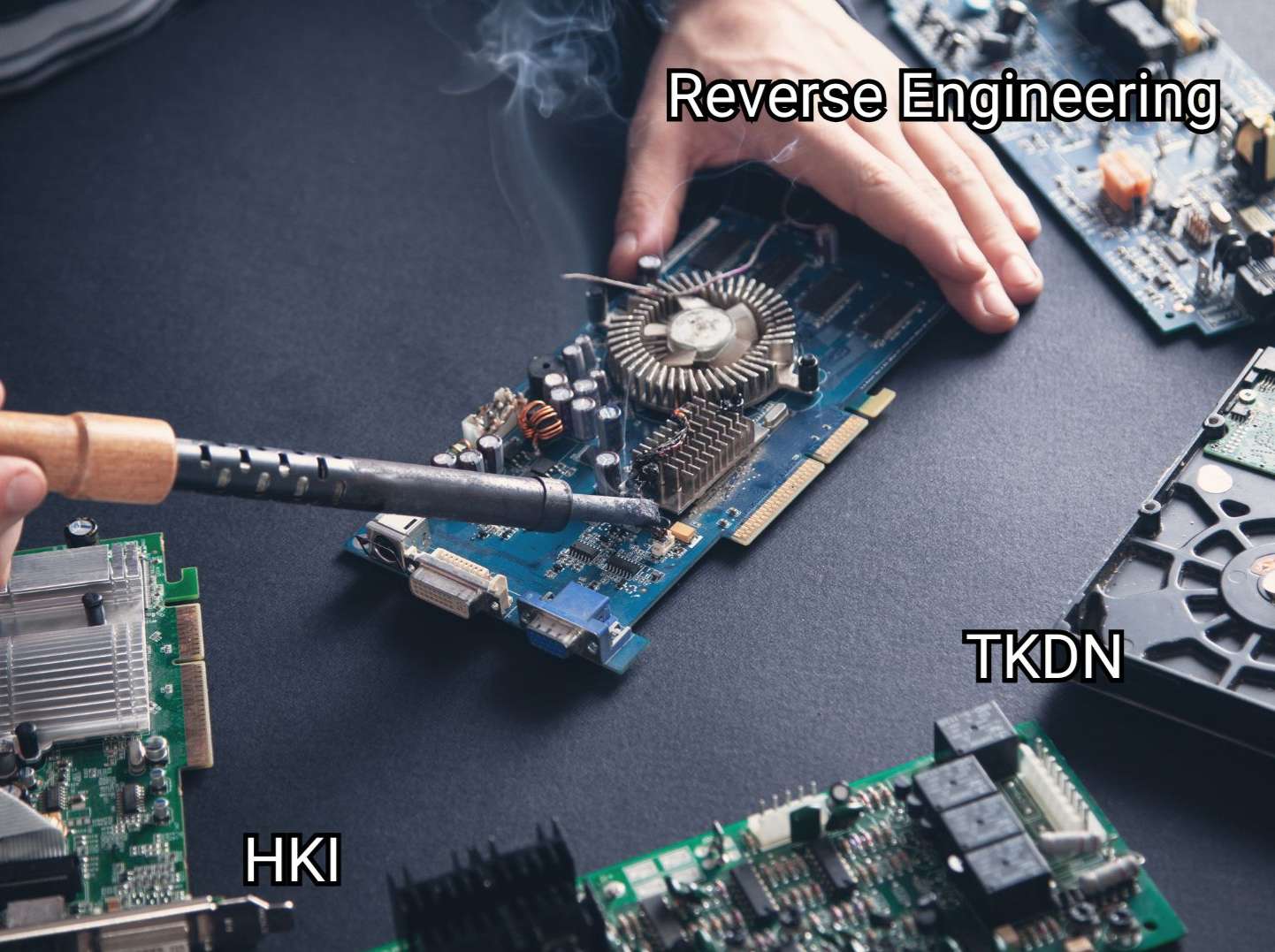
Dalam upaya mendorong kemandirian industri nasional, pemerintah Indonesia mewajibkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan ini mendorong pelaku industri untuk tidak hanya merakit, tetapi juga memproduksi secara lokal komponen-komponen penting, sehingga memperkuat rantai pasok domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Namun, dalam proses substitusi komponen impor, banyak pelaku industri melakukan reverse engineering terhadap komponen impor guna memahami, meniru, dan memproduksi ulang komponen tersebut secara lokal. Meskipun secara teknis hal ini dapat meningkatkan TKDN, jika tidak dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum, reverse engineering dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) seperti paten, desain industri, atau lisensi perangkat lunak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri yang sedang memperdalam penggunaan TKDN di tengah tuntutan efisiensi dan kecepatan produksi.
Reverse engineering adalah proses membongkar, menganalisis, dan memahami cara kerja suatu produk atau komponen untuk tujuan perbaikan, replikasi, atau pengembangan produk baru. Aktivitas ini dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari membedah struktur fisik komponen (structural), menganalisis fungsi sistem (functional), hingga membongkar perangkat lunak atau firmware (software reverse engineering). Ada pendekatan black-box, di mana sistem hanya diamati dari luar tanpa dibongkar, dan white-box, yang memberi akses penuh ke seluruh struktur sistem.
Salah satu sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) paling terkenal dalam industri teknologi terjadi antara Apple Inc. dan Samsung Electronics. Kasus ini bermula pada tahun 2011 ketika Apple menggugat Samsung karena diduga meniru desain dan teknologi iPhone dalam produk Galaxy. Apple menuduh Samsung melakukan praktik reverse engineering terhadap elemen-elemen kunci seperti bentuk fisik dengan sudut membulat, tata letak antarmuka pengguna, dan fitur multi-touch seperti pinch-to-zoom. Gugatan ini tidak hanya berlangsung di Amerika Serikat, tetapi juga memicu “patent war” di berbagai negara, termasuk Korea Selatan, Jepang, dan Jerman.
Apple mengajukan gugatan atas pelanggaran desain paten, utility paten, dan hak dagang (trade dress) yang menjadi identitas produknya. Pada tahun 2012, pengadilan federal di California memutuskan Samsung bersalah dan menjatuhkan ganti rugi sebesar USD 1,05 miliar kepada Apple. Namun, kasus ini berlarut-larut karena Samsung mengajukan banding, sehingga jumlah ganti rugi sempat berubah beberapa kali. Setelah tujuh tahun proses hukum yang panjang, kedua perusahaan akhirnya mencapai penyelesaian damai pada 2018, dengan Samsung tetap diwajibkan membayar ratusan juta dolar AS (angka pastinya dirahasiakan).
Kasus ini menjadi preseden global yang menegaskan bahwa reverse engineering yang melanggar batas perlindungan paten dapat berujung pada konsekuensi hukum dan kerugian finansial besar. Selain itu, sengketa ini mendorong perusahaan di berbagai sektor untuk lebih berhati-hati dalam mengembangkan produk agar tidak melanggar desain, teknologi, dan identitas merek pesaing. Bagi industri, kasus ini adalah pengingat bahwa inovasi harus dibangun di atas riset mandiri atau kerja sama yang sah, bukan sekadar meniru teknologi yang telah dilindungi HKI.
Di Indonesia, sejumlah produsen suku cadang mencoba menggantikan komponen asing dengan versi lokal melalui reverse engineering untuk mengejar persyaratan TKDN. Namun, beberapa di antaranya menghadapi tantangan hukum karena komponen tersebut masih dilindungi paten aktif atau terikat perjanjian lisensi dengan pihak asing.
Sebagai contoh praktik legal yang patut ditiru, beberapa industri komponen otomotif di Indonesia telah menjalin kerja sama resmi dengan prinsipal kendaraan bermerek asing. Dalam kerja sama ini, perusahaan lokal diberikan izin untuk memproduksi komponen tertentu di dalam negeri. Meskipun desain teknis dan spesifikasi berasal dari prinsipal (OEM), lisensi resmi diberikan sehingga seluruh aktivitas produksi sah secara hukum dan mendukung pencapaian TKDN. Dalam skema ini, industri dalam negeri tetap melakukan proses manufaktur, quality control, dan pengujian di dalam negeri, namun tetap menjaga kepatuhan terhadap hak kekayaan intelektual dari pihak pemberi lisensi. Hal ini tidak hanya mempercepat transfer teknologi, tapi juga memberi ruang bagi tumbuhnya kapasitas produksi nasional secara berkelanjutan.
Selain risiko pelanggaran HKI akibat reverse engineering yang tidak legal, pasar suku cadang di Indonesia juga diwarnai oleh maraknya peredaran suku cadang palsu. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Noertjahjo Darmadji, Dirut PT Astra Daihatsu Motor (ADM) dikutip dari berbagai media, dari total nilai transaksi suku cadang otomotif yang mencapai Rp 4,25 triliun per tahun, sekitar 17 persen atau Rp 722,5 miliar merupakan pasar suku cadang palsu. Sebagai perbandingan, 38 persen (Rp 1,62 triliun) dikuasai oleh komponen asli dari pemegang merek, sementara 45 persen (Rp 1,92 triliun) merupakan pasar suku cadang imitasi yang diproduksi dengan merek sendiri oleh pihak ketiga.
Tingginya peredaran suku cadang palsu ini tidak hanya merugikan pemegang merek seperti ADM (Astra Daihatsu Motor), tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan bagi konsumen. ADM memperkirakan kerugian akibat pemalsuan ini sebagai opportunity loss sekitar 12% dari target penjualan. Jika pemalsuan dapat ditekan, ADM yakin penjualan bisa 1,5 kali lebih besar. Fenomena ini terjadi karena besarnya potensi bisnis suku cadang otomotif. Dengan asumsi setiap kendaraan membutuhkan biaya penggantian suku cadang sebesar Rp 1,5 juta per bulan, nilai pasar yang mencapai triliunan rupiah memicu praktek ilegal ini.
Lebih memprihatinkan, tren pemalsuan suku cadang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, sementara sebagian besar pengguna kendaraan tidak menyadari bahaya ini. Oleh karena itu, selain mendorong peningkatan TKDN, pemerintah dan aparat penegak hukum juga harus lebih serius menangani masalah pemalsuan untuk menciptakan ekosistem industri yang sehat.
Saat ini kesadaran pelaku industri terhadap batasan hukum HKI masih rendah. Belum adanya panduan resmi tentang reverse engineering juga menimbulkan kebingungan. Beberapa perusahaan kecil mencoba mereplikasi komponen tanpa mengetahui bahwa desain atau teknologi tersebut masih dilindungi. Jika aktivitas ini dilakukan dalam skema pengadaan pemerintah, potensi gugatan hukum bisa sangat merugikan, bahkan berisiko membatalkan kontrak proyek.
Pemerintah perlu menyusun regulasi dan panduan resmi terkait reverse engineering untuk mendukung TKDN secara legal. Panduan ini harus mencakup prosedur audit status paten dan lisensi, serta mekanisme kerja sama dengan pemegang merek melalui skema lisensi manufaktur dan transfer teknologi.
Selain itu, Indonesia Manufacturing Center (IMC) dapat berperan strategis sebagai pusat layanan rekayasa ulang yang mengombinasikan analisis teknis dan hukum. IMC juga dapat menyediakan basis data komponen yang aman diproduksi secara lokal, mengembangkan pelatihan SDM tentang etika reverse engineering, dan memperkuat kemitraan industri dengan pemegang teknologi asing untuk mempercepat penguasaan teknologi.
Reverse engineering adalah alat penting untuk mendukung TKDN, tetapi harus dilakukan secara sah agar tidak melanggar HKI. Di sisi lain, maraknya suku cadang palsu memperlihatkan urgensi penegakan hukum dan penguatan pengawasan pasar. Dengan panduan yang jelas, kolaborasi industri, dan peran strategis IMC, Indonesia dapat membangun ekosistem industri berbasis teknologi yang legal, aman, dan berdaya saing global.

Anda belum login